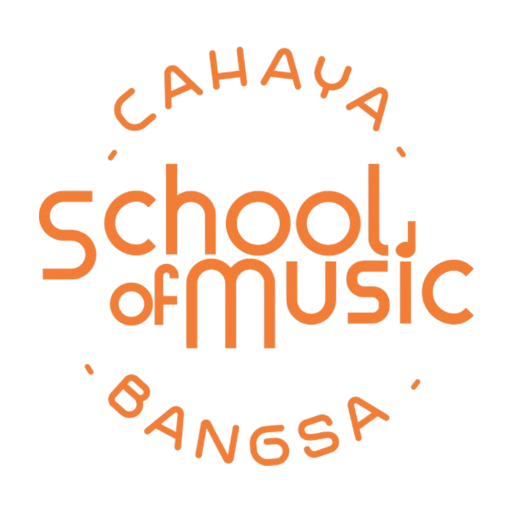Apa yang terjadi di Sumatera hari ini bukanlah bencana alam yang lahir secara alamiah, melainkan hasil langsung dari serangkaian kebijakan yang secara moral dan ekologis tidak layak disebut bijaksana. Hutan-hutan Sumatera yang dahulu berfungsi sebagai penyangga kehidupan—menjaga keseimbangan air, iklim, dan keanekaragaman hayati—telah digunduli secara masif, brutal, dan sistematis. Penggundulan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sempit, lalu digantikan dengan perkebunan kelapa sawit yang secara ekologis tidak memiliki fungsi yang setara dengan hutan alami.
Kelapa sawit bukanlah hutan. Ia adalah monokultur. Ia tidak mampu menyerap air seperti hutan hujan tropis, tidak menyediakan habitat bagi ribuan spesies, dan tidak menjaga siklus ekologis yang kompleks. Ketika hutan alami hilang dan diganti oleh sawit, maka yang terjadi bukanlah transformasi, melainkan amputasi ekosistem. Akibatnya, keseimbangan alam terganggu secara ekstrem: banjir bandang, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, hingga krisis sosial yang menimpa masyarakat adat dan lokal. Banyak wilayah di Sumatera yang tidak hanya kehilangan hutannya, tetapi juga kehilangan masa depan ekologisnya—bahkan identitas eksistensialnya sebagai ruang hidup.
Ironi terbesar dari tragedi ini adalah klaim bahwa semua ini dilakukan demi “pertumbuhan ekonomi”. Pertumbuhan bagi siapa? Keuntungan yang dihasilkan dari ekspansi sawit tidak terdistribusi secara adil, melainkan terkonsentrasi di tangan segelintir elite ekonomi dan korporasi besar. Di sisi lain, masyarakat lokal justru menanggung dampak terberat: kehilangan tanah, sumber air tercemar, ruang hidup menyempit, dan meningkatnya risiko bencana. Di sinilah terlihat kontras yang sangat tajam antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan moral—di mana yang satu dipuja, sementara yang lain dikorbankan.
Lebih jauh lagi, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya sistem perizinan, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU). Perizinan yang begitu longgar, tidak transparan, dan minim pengawasan menjadi indikasi kuat bahwa masalah ini berakar pada praktik korupsi yang mengakar. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan publik dan alam, justru berubah menjadi fasilitator perampasan ruang hidup. Ketika izin diberikan tanpa kajian lingkungan yang serius, tanpa partisipasi masyarakat, dan tanpa akuntabilitas, maka bencana yang terjadi sesungguhnya telah direncanakan sejak awal.
Dalam konteks ini, sulit untuk menutup mata dari fakta bahwa yang terlibat dalam perusakan ini bukan sekadar “pelaku ekonomi”, melainkan aktor-aktor yang gagal secara etis dan spiritual. Mereka yang dengan sadar merusak alam demi kepuasan dan keuntungan pribadi menunjukkan kemiskinan batin—ketidakpedulian terhadap sesama manusia, generasi mendatang, dan keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Ini bukan hanya soal hukum yang dilanggar, tetapi soal nilai kemanusiaan yang runtuh.
Dengan demikian, sangat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa perizinan yang lunak dan kompromistis terhadap kepentingan kapital adalah salah satu akar utama dari tragedi ekologis di Sumatera. Selama alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas, dan selama kebijakan publik dikendalikan oleh kepentingan modal, maka bencana akan terus berulang—bukan sebagai kecelakaan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem yang rusak.
Patut sekali di pertanyakan mengenai perizinan dan akses yang begitu lemah sehinnga hal seperti ini terjadi dan banyak sekali bukti sebagai berikut
link di atas adalah salah satu contoh kasus dari ratusan kasus lainya
Untuk mengatasi krisis ekologis yang terjadi di Sumatera, langkah paling mendasar dan mendesak adalah melakukan rekonsiliasi menyeluruh terhadap sistem perizinan yang selama ini lemah, longgar, dan sarat kepentingan. Seluruh izin, khususnya Hak Guna Usaha (HGU), harus ditinjau ulang secara transparan dan independen, bukan sekadar diperpanjang secara administratif tanpa evaluasi ekologis dan sosial yang serius. Izin-izin yang terbukti melanggar tata ruang, merusak kawasan lindung, atau mengabaikan hak masyarakat adat dan lokal harus dicabut tanpa kompromi.
Penguatan perizinan tidak boleh dimaknai sebagai penambahan birokrasi semata, melainkan sebagai penegakan prinsip kehati-hatian ekologis. Setiap kebijakan pengelolaan lahan harus berbasis pada kajian lingkungan hidup yang ketat, ilmiah, dan terbuka untuk publik. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak boleh lagi menjadi formalitas atau alat legitimasi proyek, tetapi harus menjadi instrumen pengendalian yang benar-benar menentukan boleh atau tidaknya sebuah kegiatan ekonomi dijalankan.
Selain itu, negara harus berhenti memposisikan diri sebagai pelayan kepentingan kapital dan kembali mengambil peran sebagai penjaga kepentingan bersama. Kebijakan pengelolaan hutan dan lahan harus berpihak pada keberlanjutan jangka panjang, bukan keuntungan jangka pendek. Ini termasuk pembatasan ekspansi perkebunan monokultur, penetapan moratorium permanen di kawasan hutan primer dan gambut, serta pemulihan ekosistem yang telah rusak melalui program restorasi yang nyata dan terukur.
Kebijakan yang lebih baik juga harus melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Masyarakat adat dan lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan hak kelola rakyat bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga strategi ekologis yang terbukti lebih berkelanjutan dibandingkan pengelolaan berbasis korporasi semata.
Di sisi lain, penegakan hukum harus diperkuat secara tegas dan konsisten. Pelanggaran lingkungan tidak boleh lagi diselesaikan dengan denda ringan atau kompromi politik. Korporasi dan pejabat yang terlibat dalam perusakan ekologis harus dimintai pertanggungjawaban pidana, administratif, dan moral. Tanpa keberanian untuk menghukum pelaku utama, kebijakan sebaik apa pun akan runtuh di tingkat implementasi.
Pada akhirnya, perbaikan perizinan dan kebijakan bukan hanya persoalan teknis, melainkan pilihan etis dan politik. Negara harus menentukan apakah ia berpihak pada keberlangsungan kehidupan atau terus tunduk pada logika akumulasi kapital. Tanpa perubahan arah kebijakan yang radikal dan berani, Sumatera akan terus menjadi korban dari sistem yang mengorbankan alam demi keuntungan segelintir pihak.
Terapkan Prinsip Least Privilege (Hak Akses Minimum)
- Akses Terbatas: Pastikan pengguna hanya memiliki izin akses ke data/fitur yang mutlak diperlukan untuk pekerjaan mereka, tidak lebih.
- “Deny by Default”: Secara default, semua akses harus ditolak. Izin hanya diberikan secara eksplisit kepada pengguna atau peran yang membutuhkannya
Implementasikan Kontrol Berbasis Peran (RBAC)
- Peran yang Jelas: Buat peran (roles) seperti admin, editor, dan penonton, lalu definisikan izin untuk setiap peran tersebut, bukan per individu.
- Tinjauan Rutin: Tinjau dan audit izin pengguna secara berkala (misal: setiap 3-6 bulan) untuk memastikan tidak ada “permission creep” (penumpukan izin yang tidak lagi diperlukan).
Amsal 29:2 (TB): “Apabila orang benar meraja, rakyat bersukacita, tetapi apabila orang fasik memerintah, rakyat mengeluh.”.